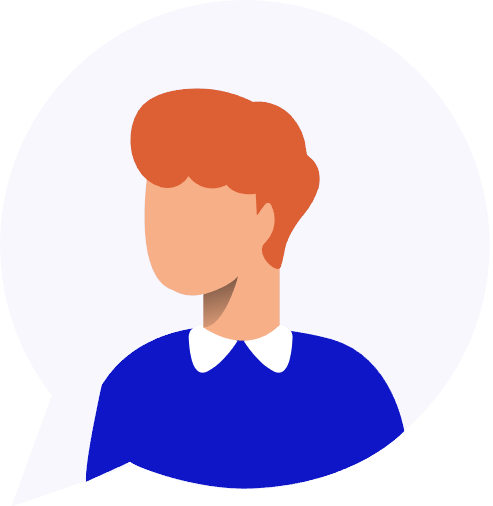Kecerdasan Literasi
Posted at : 2022-08-14 20:09:51
Kecerdasan Literasi
Di zaman informasi seperti saat ini, hal yang sulit bukanlah mencari informasi, akan tetapi memilih dan mengolahnya sengingga menjadi informasi yang bernilai. Jangan terlalu bangga dengan kuantitas informasi yang dimiliki, bisa jadi itu akan tidak berarti apa-apa atau disfungsional. Dalam skala organisasi, sekarang ini banyak perpustakaan beralih menjadi museum buku dan lembaga repositori menjadi museum informasi. Hal tersebut terjadi karena informasi yang dimiliki tidak termanfaatkan sehingga menjadi idle information. Lebih baik memiliki informasi yang tidak banyak tapi berharga daripada memiliki jutaan informasi tapi tidak berharga. Bukankah lebih baik memiliki segenggam berlian daripada sekarung pasir? Idealnya memang memiliki informasi banyak dan berharga semuanya.
Menguasai informasi merupakan syarat utama untuk menjadi manusia yang berpengetahuan. Akan tetapi banyak informasi belum tentu juga bisa mengakselerasi pemahaman. Bayangkan!, pada tahun 2012 jumlah data dan informasi yang dihasilkan dan direplikasi diperkirakan mencapai lebih dari 2,8 zetabita atau sekitar 2,8 triliun gigabita. Tingkat pertumbuhan data mencapai sembilan kali lipat dalam waktu lima tahun. Angka ini diperkirakan terus meningkat hingga 50 kali lipat pada tahun 2020 (Livikacansera, 2016)
Kita tidak harus mengetahui semua hal tentang sesuatu agar memahaminya. Terkadang terlalu banyak fakta seringkali sama-sama menghambat pemahaman seperti juga terlalu sedikit fakta. Bahkan ada kesan bahwa terlalu dibanjiri oleh informasi sehingga menghancurkan pemahaman. Adler (2011) mengatakan yang dimaksud dengan belajar adalah memahami lebih banyak, bukan mengingat lebih banyak informasi yang tingkat keterpahamannya (intelligibility) sama dengan informasi lain yang sudah Anda miliki. Montaigne berbicara tentang “an abecedarian agnorance that precedes knowledge, and another doctoral ignorance that comes after it.” Yang pertama adalah ketidaktahuan orang-orang yang sama sekali tidak bisa membaca karena buta huruf. Yang kedua adalah ketidaktahuan orang-orang yang banyak membaca buku denga cara yang salah. Mereka, seperti dikatakan Paus Alexander, adalah orang-orang pandir yang banyak membaca buku akan tetapi dengan cara yang bodoh.
Sekarang ini banyak pusat repositori yang terobsesi untuk membangun data yang besar (big data). Tentu saja itu adalah hal yang baik dan positif sepanjang fungsional. Akan tetapi harus dipertimbangkan juga apakah dengan adanya google dan mesin pencari (search engine) lainnya big data yang ada di sebuah lembaga repositori masih diperlukan. Mengapa tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah ada saja. Apabila masalah privasi dan eklusivitas masih menjadi pertimbangan, justru akan bertentangan dengan demokratisasi informasi yang apabila dinegasikan akan merugikan diri sendiri.
Supaya tidak terjebak kepada kesia-siaan maka diperlukan keterampilan memilih informasi dan mengelolanya menjadi informasi yang berharaga, yang saya sebut dengan kecerdasan literasi. Bayangkan, setiap hari milyaran informasi diproduksi baik oleh perorangan maupun lembaga, sehingga kita bagaikan berenang di lautan informasi dan mungkin juga menjadi tenggelam di dalamnya. Tanpa kecerdasan informasi alih-alih kita akan mendapat kemudahan malah mungkin akan terlibas dan tertelan gelombang informasi. Kecerdasan literasi ibarat papan selancar yang akan membawa kita mengarungi irama gelombang dari lautan informasi.
Kecerdasan informasi mutlak diperlukan terutama oleh lembaga repositori supaya koleksi informasi yang tersedia dapat disintesiskan, disajikan, dan didesiminasikan menjadi informasi yang aktual dan bernilai. Lebih jauh, dengan kecerdasan informasi, lembaga repositori menjadi lembaga yang antisipatif terhadap perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan muncul dan menjadi trend di masa yang akan datang.
Empat Pilar
Lebih dari dua puluh tahun yang lalu seorang futurolog Alvin Toffler mengatakan bahwa sekarang ini adalah dekade gelombang ketiga yaitu gelombang informasi. Pada era ini kegiatan ekonomi akan berbasis kepada pengetahuan atau knowledge based economy, di mana informasi akan menjadi komoditas yang sangat menentukan. President of Microsoft Amerika Latin Herman Rincon bahkan menyamakan data sebagai mata uang baru. Masih menurut Rincon, sekitar 90 persen dari seluruh data yang ada saat ini tercipta hanya dalam waktu dua tahun terakhir. Dari aspek bisnis, nilai pasar global big data diprediksi mencapai 53,4 miliar dolar AS pada tahun 2017.
Seharusnya lembaga yang akan berperan dan tentu saja yang disangka akan mendapat banyak keuntungan adalah perpustakaan dan lembaga repositori. Karena lembag-lembaga inilah yang mengakumulasi pengetahuan dan informasi. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Lembaga-lembaga tersebut tetaplah seperti business as usual, malah semakin hari lembaga ini semakin tergerus peran dan posisinya, bahkan sudah banyak yang mati atau bubar. Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga pengetahuan ini hanya mengkoleksi sumber informasi dan pengetahuan bukan mengolohnya menjadi informasi baru yang bernilai. Kebanyakan lembaga repositori yang ada sekarang ini ibarat pasar tradisional yang menyediakan berbagai macam jenis informasi. Dan dengan pasif menunggu pembeli yang datang. Dalam prosesnya, sebagian besar lembaga ini hanya membuat klasifikasi sumber informasi berdasarkan kepada jenis informasi bukan berdasarkan kepada nilai informasinya.
Secara teknis Yanuar Nugroho dan Luis Crouch (2016) memberikan formulasi supaya data dan informasi menjadi fungsional atau berharaga: pertama, gunakan lebih banyak disaggregeted data (data yang dapat dipilah-pilah). Kedua, fokus pada input yang membuahkan hasil kahir positif, berdasarkan bukti, data, ataupun penelitian. Ketiga, mendorong inovasi dan kolaborasi antar berbagai sektor. Keempat, memastikan bahwa masyarakat sipil serta pemerintah pusat dan daerah menggunakan data untuk mengambil keputusan. Empat langkah terknis formulasi tersebut bisa dilakukan apabila dibarengi dengan kecerdasasn literasi yang memadai.
Untuk meraih kecerdasan literasi minimal diperlukan empat pilar utama yang sangat fundamental: pertama, tradisi membaca. Kecerdasan literasi akan dimiliki hanya oleh orang-orang yang memiliki tradisi membaca yang baik. Malah, apabila tradisi membaca sudah terpateri atau sudah menjadi karakter dalam diri seseorang dengan sendirinya pasti orang tersebut memiliki kecerdasal literasi. Tentu saja bukan hanya membaca, akan tetapi dengan sistematika dan perencanaan yang baik. Memiliki banyak informasi kalau tidak fungsional atau tidak saling berkorelasi tidak akan menghasilkan output yang bernilai. Tradisi membaca adalah pilar utama untuk memperoleh kecerdasaran literasi. Jangan bermimpi memiliki kecerdasar literasi tanpa memiliki tradisi membaca yang baik.
Kedua, manajemen pikiran. “Anda adalah apa yang anda pikirkan” kata Carnegie. Artinya pikiran adalah akar dari perilaku manusia. Tindakan atau prilaku seseorang tidak mungkin keluar dari bingkai pikirannya. Oleh karena itu, untuk membangun karakter langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas pikiran. Dan kualitas pikiran sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang masuk ke dalam benak yang kemudian diproses menjadi ide atau gagasan.
Input informasi yang salah otomatis akan mengeluarkan output yang berupa ucapan atau perbuatan yang juga salah. Perilaku seseorang tidak akan keluar dari perintah pikiran, walaupun informasi yang membentuk pikiran kita adalah informasi yang salah. Tidak jarang konflik terjadi karena misinformasi atau mendapatkan informasi yang keliru (hoax) melalui intrik atau isu yang kebenarannya tidak bisa dipertanggung-jawabkan.
Oleh karena itu, biasakanlah diri untuk mengetahui sesuatu sebagaimana ia adanya, secara akurat, dan objektif yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan secara benar, kecuali jika mempunyai pengetahuan yang benar tentang sesuatu tersebut.
Selain mempunya daya serap yang selektif terhadap informasi, juga harus memiliki kemampuan berpikir secara meluas dengan informasi yang general dan mendalam dengan informasi yang bersifa spesialis. Yang pertama lebih berorientasi pada keluasan cakupannya, sedangkan yang kedua lebih berorientasi pada kedalamannya. Yang pertama berorientasi pada pembentukan wawasan, sedangkan yang kedua lebih berorientasi pada penguasaan detil. Yang pertama memberi efek integralitas, yang kedua memberi efek ketepatan. Idealnya seorang pekerja informasi atau pustakawan memiliki kemahiran dalam menggabungkan kedua metode berpikir tersebut supaya memiliki informasi yang komprehensif, bersifat lintas disiplin, dan generalis dengan penguasaan yang tuntas terhadap satu bidang ilmu sebagai spesialisasinya.
Ketiga, metode analisis informasi. Metode analisis informasi ada dua jenis: kualitatif dengan teknik interpretasi misalnya analisis wacana dan analisis framing, sedangkan metode yang kuantitatif biasanya memakai analisis isi. Metode kualitatif memerlukan keluasan pengetahuan atau referensi (frame of reference) serta kekayaan pengalaaman (field of experience). Sementara metode kuantitatif memerlukan ketepatan perhitungan yang biasanya menggunakan statistik. Tentu saja untuk mendapatakan hasil analisis yang integral perlu memakai pendekatan kedua metode tesebut.
Analisis informasi diperlukan untuk mendaptkan informasi yang lebih mendekati kebenaran dan ketepatan. Karena antara teks dan konteks selalu ada mediasi yang terkadang bisa membuat bias. Kata Barthes (2000) teks terdiri bukan hanya barisan kata-kata yang melepaskan pesan dari pengarangnya, tetapi suatu ruang multidimensi di mana telah dikawinkan dan dipertentangkan beberapa tulisan, tidak ada yang asli darinya. Teks adalah suatu tenunan dari kutipan, berasal dari seribu sumber budaya.
Selain harus memperhatikan pengarangnnya, dalam membaca sebuah karya, Jean Paul Sartre (2000) mengingakan pada kita bahwa teks tidak bisa lepas dari konteksnya. Suatu karya adalah anak kandung zaman. Sebuah buku punya kebenaran mutlak dalam zamannya. Buku muncul dari inter-subjektivitas, ikatan hidup nafsu amarah, kebencian atau cinta antara orang-orang yang menghasilkannya (penulis) dan orang-orang yang menerimanya (pembaca).
Keempat, inovasi. Informasi yang sudah terakumulasi kemudian dipahami dan dicerna secara objektif melalui analisis yang intergral. Informasi yang telah diurai melalui pisau analisis tersebut kemudian dibangun dan diintegrasikan atau menghubngkan bagian-bagian yang terpisah dari peristiwa atau kenyataan menjadi kesatuan yang terkorelasi secara utuh. Maka dari situlah akan melahirkan informasi atau gagasan baru yang merupakan tambahan atas informasi atau pikiran yang semula sudah ada. Itulah inovasi informasi.
Kecerdasan literasi dapat memperlancar dalam pengelolalaan pengetahuan yang pada akhirnya bisa berkontribusi untuk memperlancar pembelajaran organisasi. Pengelolaan pengetahuan adalah perihal bisnis keilmuan. Gagal mengelola pengetahuan akan menjadikan bisnis keilmuan mengalami kebangkrutan substantif. Jika ini terjadi, peradaban sebuah bangsa akan sulit menjauh dari titik nadir. Sebab, menurut Kidwell, Lide, dan Johnsson “mengelola pengetahuan pada prinsipnya adalah mengubah informasi dan aset intelektual ke dalam nilai abadi” (Muzakki, 2016). Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kecerdasan literasi merupakan keniscayaan baik bagi individu maupaun organisasi, terutama institusi informasi.
Dengan waktu yang terbatas tidak mungkin untuk mengikuti atau membaca informasi yang tersedia. Akan tetapi dengan memiliki kecerdasan literasi kita bisa mendapatkan informasi yang mememadai. Dengan kecerdasana literasi pula, dalam konteks organisasi, sebuah perpustakaan atau pusat repositori akan mudah dalam melakukan menajemen informasi. Informasi yang masuk melalui kegiatan akusisi diproses berasarkan nalar yang kritis dan objek kemudan direkonstruksi dan akhirnya melahirkan luaran (output) berupa informasi baru yang inovatif dan bernilai.
Sepertinya hanya dengan kecedasan literasi inilah pusat informasi, perpustakaan, dan lain-lain institusi informasi akan terhindar dari kematiannya digilas oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin akseleratif dan massif.