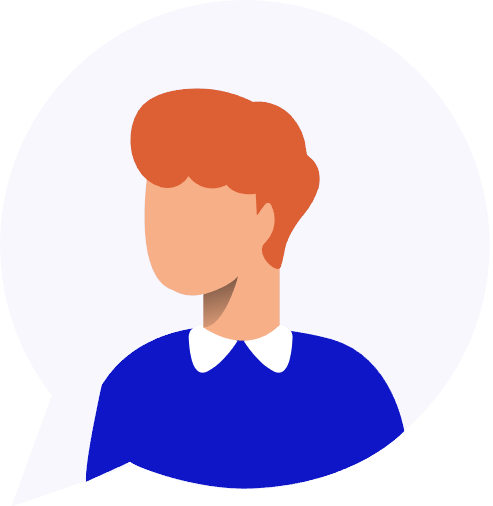menganalisis warisan literasi karya para penulis nusantara di masa lalu
Posted at : 2022-08-14 20:09:02
Literasi Sains
Ada hal menarik dari hasil menganalisis warisan literasi karya para penulis nusantara di masa lalu. Ternyata karya-karya mereka yang terkenal sampai sekarang hampir semuanya berkaitan dengan masalah kekuasaan atau politik dan filsafat moral. Saya tidak menemukan tulisan yang berkaitan dengan hasil pengamatan terhadap fenomena alam dan meteri atau saintifik. Misalnya, nenek moyang kita memiliki kemampuan membuat keris yang indah akan tetapi yang banyak dibahas adalah dari aspek seni, filosofi, dan magisya bukan dari aspek teknologinya. Candi Borobudur sampai hari ini masih misteri secara teknologi karena tidak ada dokumentasi ilmiah yang terwarisi.
Sampai hari ini pun masyarakat kita belum memiliki budaya litrasi Iptek. Riset yang dilakukan oleh Kompas (2008) menyimpulkan bahwa tema sains belum menjadi favorit. Pusat Riset dan Pengembangan Literatur Keagamaan Depag (2012) memberikan data tentang manuskrip nusantara yang berhasil dikumpulkan ternyata tema yang paling banyak adalah mengenai sufisme (603), disusul dengan hagiografi tradisional (484) dan dongeng (331), dll. Seluruh bidang yang berkaitan dengan sains tidak lebih dari 100 buah. Yang terbaru dilakukan oleh YouGov tentang lemahnya literasi sains. Survei yang dilakukan di 23 negara menempatkan masyarakat Indonesia di urutan tertinggi yang tidak percaya pemanasan global dipicu manusia. Fenomena ini bisa berimplikasi pada kurangnya tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan (Kompas, 13 Mei 2019)
Lemahnya budaya literasi sains berdampak kepada lemahnya kinerja dan capaian bidang strategis terutama bidang penelitian, inovasi (Indonesia berada di peringkat 97 dari 141 negara, Global Innovation Index 2015) dan lemah daya saing bangsa (Indonesia berada di poisisi 37 dari 56 negara, The Global Competitiveness Report 2015-2016). Di samping itu, lemahnya literasi ilmu pengatahuan juga berdampak kepada pengangguran dan kemiskinan; perilaku perundungan (bullying), fundamentalisme, dan radikalisme; serta sangat rentannya masyarakat terpapar berita bohong (hoax) atau post-truth dan antisains. Secara personal lemahnya budaya literasi juga mengakibatkan lemahnya kemandirian bahkan berpengaruh terhadap kejiwaan.
Menurut saya itulah salah satu penyebab Indonesia belum menjadi negara maju sampai sekarang. Negara yang abai terhadap pembangunan budaya literasi Iptek akan dikutuk menjadi negara terbelakang sampai langit runtuh. Yunani misalnya, bangsa yang asalnya menjadi soko guru peradaban dunia—negeri para filsuf itu—kini menjadi negara gagal (failed state) karena terlilit utang. Yunani gagal mentrasformasi diri dari bangsa filosofis menjadi bangsa yang pragmatis. Sejarah banyak memberikan bukti bahwa jarang sekali ada filsuf yang hidupnya kaya, kalau yang menjadi gila banyak.
Dari dahulu sampai hari ini imperialisme dan kolonialisme pada hakikanya adalah perang Iptek bukan sekadar perang ideologi. Bangsa kita dijajah sampai berabad-abad lamanya pada hakikatnya adalah kuasa literasi sans atas budaya non-sains. Tom Pires (1465-1540), Cornelis de Houtman (1565-1599), dan Jan Huygen van Lin-schoten (1563-1611) adalah para penjelajah dunia yanag menemukan rute nusantara sebagai pembuka pintu penjajahan. Mereka semua tidak kesasar bertandang ke nusantara karena atas petujuk sains bukan hasil perdukunan. Akhirnya VOC datang ke nusantara pada tahun 1602, bukan hanya berbekal kapital saja tapi juga kapalnya penuh dengan senjata canggih—sebagai produk ilmu pengetahuan—yang digambarkan seperti panggung senjata di atas laut. Setelah itu menyusul para ilmuwan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekakayaan nusantara demi kapital mereka.
Kegiatan ilmiah di Indonesia diawalai pada abad ke-16 oleh Jacob Bontius yang mempelajari flora Indonesia dan Rompius dengan karyanya yang terkenal berjudul Herbarium Amboinese. Pada akhir abad ke-18 dibentuk Bataviaasch Genotschap van Wetenschappen. Dalam tahun 1817, C.G.L. Reinwardt mendirikan Kebun Raya Indonesia (S'land Plantentuin) di Bogor. Pada tahun 1928 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie. Kemudian tahun 1948 diubah menjadi Organisatie voor Natuurwetenschappelijk onderzoek (Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam, yang dikenal dengan OPIPA). Akhirnya tahun 1967 menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1967.
Pada tahun 1858 Alfred Russel Wallace mengunjunga nusantara. Catatan perjalanannya (logbook) dituangkan dalam buku The Malay Archipelago (1869). Dalam buku ini ditemukan nama-nama flora dan fauna Nusantara dalam nama ilmiahnya, lengkap dengan kedudukan spesies tersebut dalam taksonomi. Persebarannya pun dijabarkan secara terperinci, lengkap dengan perkiraan perubahan lempeng bumi dan masa geologisnya. Wallace juga menggambarkan fenomena mimikri pada beberapa spesies serangga dan burung. Adakah ilmuwan kita yang memiliki logbook sebagus yang dibuat Wallace?
Sayang, yang terwarisi dari penjajah hanyalah budaya politik, birokrasi, dan feodalismenya bukan spirit saintifiknya. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang perhatian negara terhadap pembangunan literasi Iptek masih kurang. Hal ini tercermin dari prioritas pembangunan dari rezim ke rezim. Setelah 75 tahun merdeka anggaran riset baru 0,25 persen dari PDB. Sehingga ada anekdot, bangsa lain sedang berlomba mengeksplorasi bulan, tapi kita tidak bergeming karena ilmuwan Indonesia sudah terbiasa hidup merana di tengah bulan, bahkan terbiasa bertahan hidup dari bulan ke bulan—karena gajinya kecil.
Semua negara-negara besar memiliki proyek-proyek Iptek ambisius dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, energi terbarukan, dan antarikasa. Tentu saja bukan hanya pamer kekutan Iptek, yang lebih penting adalah mengajak, mendorong, dan mengarahkan pola pikir masyarakatnya supaya berbudaya ilmiah. Hari ini kita dibuat kagum sekaligus tidak berdaya oleh China yang agresif dalam perdagangan dan teknologi. China bisa maju seperti itu karena sejak lima belas tahun yang lalu menjadikan scientific literacy sebagai program negara yang secara serius dilaksankan secara terstruktur, sistematis, dan massif.
Tanpa membangun budaya literasi Iptek bangsa kita mustahil akan menjadi bangsa maju. LIPI sebagai lembaga riset terbesa di Indonesia sangat potensial untuk menjadi lokomotif dalam proyek ini. LIPI memiliki semua sumber daya yang diperlukan— ilmuwan terbanyak dan infrastruktur riset terlengkap. Tujuan utama pembangunan budaya literasi Iptek adalah untuk membangun sikap atau karakter ilmiah (scientific attitude). Supaya masyarakat Indonesia terbiasa: berpikir rasional; mengambil keputusan secara objektif yang didasarkan kepada fakta dan data; berbicara dan bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan; menyenangi hal-hal yang baru dan menikmati tantangan serta perubahan; dan selalu melahirkan gagasa-gagasan baru secara produktif.
Berlimpahnya kekayaan alam ternyata tidak menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, bahkah berbalik menjadi kutukan sumber daya atau paradoks keberlimpahan. Itu terjadi karena bangsa kita abai terhadap pembangunan budaya Iptek. Akhirnya bangsa kita menjadi bangsa “berbudaya” akan tetapi tidak berdaya.
Sebagaimana cerita Malin Kundang, apabila tidak mentrasformasi diri menjadi masyarakat berbasis Iptek, Indonesia pun akan dikutuk menjadi “batu”, benda mati yang tidak bisa berkembang, malah bisa hilang ditelan bumi (sirna ilang kertaning bumi).
*Tulisan ini dimuat di Kompas.com., 4 Agustus 2020 dengan judul "Urgensi Literasi Iptek" (Suherman)